Namaku Tio, aku tinggal di sebuah gubuk sederhana yang letaknya cukup jauh dari pemukiman warga. Di gubuk ini hanya ditempati olehku dan Nenekku yang kini usianya menginjak 80 tahun. Ayahku sudah meninggal sejak aku berusia 2 tahun. Sepeninggal Ayah, Ibu lah yang bertugas mencari uang untuk makan kami sehari-hari.
Selain Ibuku, Nenek tidak mempunyai anak lagi. Sebenarnya memang tidak punya. Karena Nenekku memang tidak bisa memiliki anak, alias mandul. Tapi Kakek sangat setia kepadanya. Bertahun-tahun mereka hidup tanpa anak, hingga akhirnya di suatu malam saat hujan deras, mereka menemukan seorang bayi yang sedang menangis keras di depan pintu rumah mereka. Tubuh bayi itu terlihat merah dengan sedikit pucat dan kebiru-biruan. Ya, bayi itu adalah Ibuku. Nenek dan Kakek memutuskan merawat Ibuku seperti anak mereka sendiri.
Tapi sudah 10 tahun ini Ibuku tidak pernah kembali menyapa kami lagi. Usiaku baru 8 tahun saat Ibu pamit pergi ke kota untuk bekerja. Mengadu nasib katanya waktu itu, berharap mendapat gaji dan pekerjaan yang layak dengan berbekal ijazah SMK-nya. Dua tahun pertama Ibuku masih rajin mengirim gajinya setiap dua bulan sekali lewat wesel pos. Namun setelah itu, kosong, kami tidak pernah menerima kiriman uang lagi. Hingga akhirnya Nenek menyerah pada bulan ke delapan. Berbekal sepeda tua milik almarhum Kakek, Nenekku dan aku pergi melapor pada polisi setempat, berharap para polisi itu dapat mencari dimana keberadaan Ibuku.
Sayangnya, hingga 3 tahun kemudian, kami tidak pernah mendengar kabar dari polisi tersebut. Entah mereka mencari Ibuku atau tidak. Nenekku benar-benar pasrah saat itu. Dia tidak berusaha mencari Ibuku lagi. Tubuhnya yang semakin menua membuat fisiknya melemah. Aku pun dengan terpaksa tidak menamatkan sekolah SD-ku karena keadaan keuangan yang semakin memprihatinkan. Bahkan sepeda peninggalan Kakek, satu-satunya harta kami yang tersisa harus dijual untuk mengisi perut kami yang kelaparan.
Kini usiaku 17 tahun. Cukup untuk membuatku bisa membantu nenek bekerja serabutan sebagai kuli bangunan di rumah-rumah warga atau menjadi kuli panggul di pasar. Aku tidak berani mencari pekerjaan ke luar kota, selain karena trauma atas masa lalu ku, aku juga tidak tega meninggalkan Nenek sendirian di usianya yang sudah sangat tua. Lagipula aku tidak mempunyai uang banyak untuk ongkos pergi ke kota, karena upahku bekerja serabutan selalu habis untuk biaya hidup kami.
Suara ketukan di pintu bambu rumahku menarikku pada lamunan panjangku. Segera aku beranjak untuk melihat siapa tamu pertama kami setelah bertahun-tahun kami kedatangan tamu untuk terakhir kalinya. Aku mengernyit saat aku tiba di depan pintu yang ternyata sudah terbuka, di sana berdiri seorang wanita paruh baya dengan menenteng tas jinjing lusuh ditangannya. Wajahnya terlihat lebam, di sudut bibirnya terdapat bekas luka yang sudah mengering. Aku terus memperhatikan wanita itu, memutar otak apakah aku mengenalnya.
“Cari siapa, ya?” Aku bertanya dengan nada sesopan mungkin sekalipun aku tidak mengenalnya.
“Tio … kamu Tio, kan?” Alih-alih menjawab pertanyaanku, wanita ini malah balik bertanya padaku. Tunggu … bagaimana wanita ini tahu namaku Tio? Seingatku kami tidak pernah bertemu.
“Tio, ini Ibu, Nak. Ibu.”
Deg. Mendadak tubuhku terasa kaku. Aku merasa kehilangan suara-suara di sekitarku. Rasanya hening menyergap, aku tidak siap dengan ini. Aku belum mempersiapkan hatiku untuk melihat Ibu lagi setelah 10 tahun meninggalkanku dan Nenekku dalam belenggu kemiskinan. Aku tidak siap untuk bertemu sosok yang sudah coba aku lupakan selama bertahun-tahun.
“Tio maafkan Ibu karena meninggalkanmu dan Nenek, Nak. Maaf … maaf.”
Seketika aku tersadar dari guncangan yang kurasakan tadi saat melihat wanita paruh baya ini—Ibuku—menangis.
“Masuklah dulu, Bu.” Aku memberinya jalan orang yang katanya Ibuku ini untuk masuk ke dalam gubuk. Tanpa berusaha menenangkan Ibuku yang sedang menangis, karena aku sendiri sedang terguncang.
Aku mempersilahkan Ibuku untuk duduk di atas karung bekas yang Nenekku jahit menjadi satu sebagai tikar jika sewaktu-waktu ada tamu yang berkunjung kemari. Karena lantai dari gubukku masih dari tanah. Sementara Ibuku masih menangis walau sudah tak sekeras tadi. Hanya meninggalkan sesenggukan kecil saja, aku pergi ke belakang untuk mengambil air putih dalam cangkir plastik.
“Minumlah dulu, Bu.”
Ibuku menerimanya. Dia terlihat meminumnya pelan-pelan. Setelah beberapa teguk, Ibu menatap padaku lagi. Kali ini dengan matanya yang memerah.
“Tio … maafkan Ibu, Nak, sudah pergi selama ini tanpa kabar sama sekali, Ibu—”
“Bisa jelasin ke aku selama ini Ibu pergi kemana aja? Tanpa kabar. Dan setelah sekian tahun Ibu nongol dengan keadaan seperti ini. Bisa jelaskan ke aku, Bu?” Aku menunjuk luka memar di tubuh Ibuku.
Ibu mengangguk pelan. Tampak menarik napas sesekali. Aku menatapnya serius dan prihatin, masih menunggu Ibu membuka suara.
“Setelah dua tahun tinggal di kota, Ibu akhirnya menikah lagi dengan lelaki yang menjadi rekan kerja Ibu. Herman namanya. Awalnya dia memang terlihat baik, tapi lama-kelamaan sikapnya berubah kasar. Dia sering mukul Ibu, ngambil gaji yang seharusnya dikirim untuk makan kamu dan Nenekmu di sini untuk dirinya sendiri. Ibu pernah ngelawan tapi dia—” Ibuku menarik napas dalam lagi, setetes air mata mengalir membentuk jejak panjang di pipi keriputnya, “—dia ngancem Ibu, kalau ibu ngelawan dia bakal bunuh Ibu, Tio. Makanya selama bertahun-tahun Ibu cuma diem menerima perlakuannya. Ibu takut Tio, dia selalu ngawasin gerak-gerik Ibu.”
Aku mengernyit mendengar cerita Ibuku, menahan rasa panas di mataku dan amarah yang menggedor-gedor akalku untuk segera dilampiaskan. Aku tidak pernah mengira hidup Ibu begitu menderita di perantauan. Aku kira Ibu yang memang berniat pergi, aku kira hanya aku dan Nenek saja yang menderita.
“Lalu, bagaimana caranya Ibu bisa kabur dari dia, Bu?”
“Dia pemabuk. Saat dia mabuk, diam-diam Ibu ambil sedikit demi sedikit uangnya buat ongkos pulang kampung. Dan kemarin kesempatan Ibu kabur karena Ayah tirimu ada tugas keluar kota.”
Aku diam. Merasa tidak terima Ibuku mengatakan lelaki brengsek itu adalah ayah tiriku. Aku tak sudi.
“Tio, Nenekmu mana. Ibu mau ketemu, Ibu mau sungkem di kakinya.”
“Nenek—” Belum sempat aku menjawab, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Tepat di ambang pintu, Nenek berdiri dengan seikat kayu bakar di tangannya.
“Mak ini Ijah, Mak. Ini Ijah.” Ibu tiba-tiba berdiri dan menghampiri Nenekku yang mengerjap-ngerjapkan matanya. Penglihatan Nenek memang tambah memburuk seiring bertambah usianya.
“Jah … ini kamu? Ya Allah, kemana aja kamu, Nduk.”
Akhirnya aku melihat dua orang wanita yang kusayangi itu menangis. Saling berpelukan dengan tangis tersedu-sedu yang mengiringinya. Aku terpaku di tempatku duduk. Lagi-lagi aku merasa sesak luar biasa di relung hatiku.
“Mak, Tio—”
“Tio…,” Nenek memotong kalimat Ibu dengan suara lirih. Pelukan mereka terlepas.
“Iya, Mak. Tadi Ijah—”
“Ayo ikut, Emak.”
Tanpa menunggu Ibu bicara, Nenek berjalan keluar rumah. Aku dan Ibu saling tatap, namun tak lama kami memutuskan mengikuti Nenek di belakangnya.
Cukup lama kami berjalan, akhirnya Nenek berhenti di suatu tempat yang sepertinya menjadi tujuannya. Aku tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mataku. Tatapanku sendu ke arah Ibu dan Nenekku. Aku tahu tempat ini.
“Mak, kok kita ke pemakaman. Kita mau ziarah ke makam siapa, Mak?”
“Lihat nama di nisannya, Jah.”
Ibu menurut, menatap lebih detail makam sederhana itu. “Tio Rianto.”
Aku melihat Ibu terdiam setelah membaca nama di nisan itu.
“Mak, kenapa nama Tio ditulis di sini, Mak! Kenapa Emak bawa aku ke sini!” Ibu berkata dengan suara yang terdengar emosi meski tak kentara.
“Ini memang makam Tio, Jah. Tio meninggal dua minggu lalu setelah sakit karena kejatuhan batu bata waktu nguli di rumah salah satu warga. Tio udah nggak ada, Jah.” Nenek menjelaskan dengan mata berkaca-kaca. Suaranya terdengar serak.
“Nggak Mak! Enggak! Tio anakku masih hidup, tadi aku ketemu dia, Mak! Tio ada di sini, Mak! Dia masih hidup!” Aku melihat Ibu berbicara dengan suara tinggi, nyaris berteriak, kemudian dia menatapku. Tersenyum, tapi lelehan air mata di pipinya mengatakan hal lain.
“Tio … Nak. Liat Tio, Nenekmu bilang kamu udah mati. Itu bohongkan Tio, buktinya kamu ada di sini …. Mak, liat Mak. Itu Tio anakku ada di sini, Mak. Emak kalo bercanda jangan keterlaluan!”
Aku menggigit bibir bawahku. Menahan isakan melihat betapa Ibu mencoba meyakinkan Nenek bahwa aku ada di hadapan mereka. Nyatanya hanya Ibu yang bisa melihatku.
Aku menunduk, menyadari tanganku tak sejelas dulu lagi. Kini tanganku pucat, transparan. Seluruh tubuhku terasa ringan sekarang. Dua minggu pergi tapi aku tak benar-benar pergi. Aku menunggu, entah menunggu apa. Menetap di dalam gubuk Nenekku meski ragaku di tempat lain. Menetap di dalam sana sekalipun tak pernah terlihat lagi.
Kini aku tahu apa yang kutunggu. Aku menunggu Ibu pulang. Setidaknya sebentar sebelum aku benar-benar pergi untuk selamanya.
Menyadari wujudku yang semakin hilang, Ibu menangis. Dia meraung memanggil-manggil namaku. Aku tersenyum melihatnya. Kali ini senyuman tulus. Benar-benar tersenyum sekalipun sosokku semakin hilang.
“Selamat tinggal, Bu … Nek. Hiduplah dengan bahagia.”
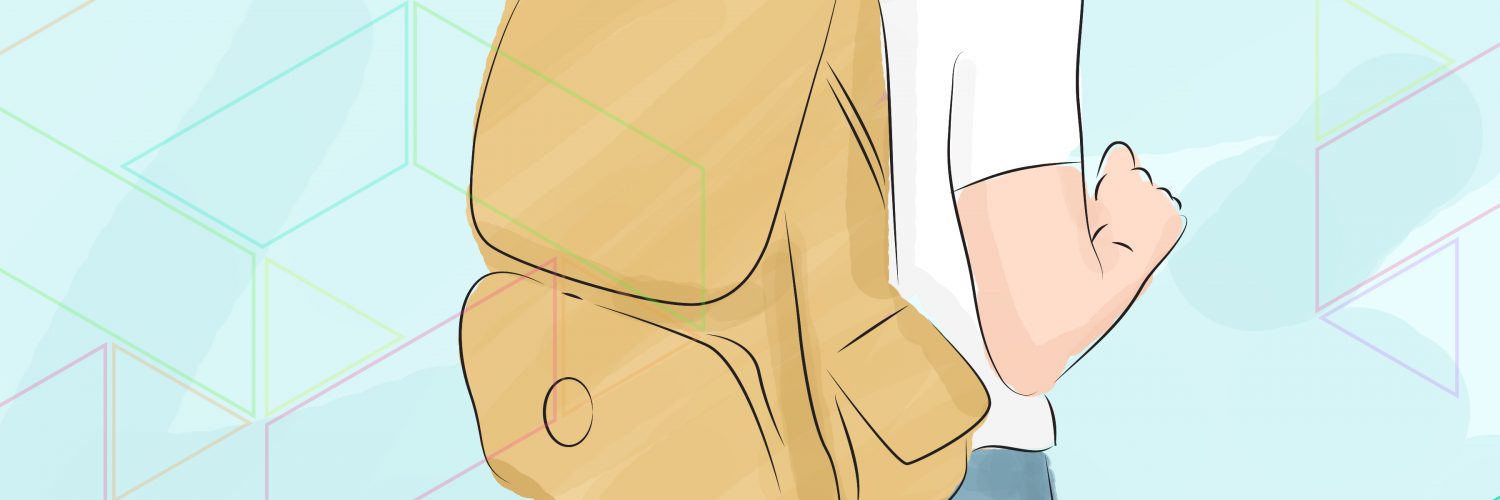






Add comment